Oleh: Man Alzalam
“Semakin banyak aku bercinta, semakin ingin aku membuat revolusi, Semakin sering aku melibatkan diri dalam revolusi, semakin ingin aku bercinta.”
-Salah satu slogan pada masa pemberontakan Paris 1968.
“Ng*ntot bukan urusan negara.”
-salah satu slogan pada momen aksi #ReformasiDikorupsi di Makassar.
Tulisan ini merupakan penghormatan penulis kepada 5 orang pahlawan pemuda yang gugur pada September lalu. Rest in power, brother.
Belakangan ini terdapat sebuah perlawanan masyarakat sipil yang didominasi oleh mahasiswa dan anak Sekolah dengan beragam poster dan spanduk tuntutan yang bernada ‘nyeleneh’. Tulisan-tulisan tuntutan bertema seksual, gaya hidup, maupun kutukan-kutukan dengan bahasa kotor, menjadi warna tersendiri di foto-foto demonstrasi yang beredar di media massa.
Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, gerakan yang terjadi belakangan ini tidak hanya memancing dukungan terhadap tuntutan-tuntutan resmi yang diajukan, namun juga memancing gelak tawa dan keceriaan dari para netizen. Betapa tidak, terdapat beberapa peserta aksi, terutama anak sekolah, yang ketimbang menuntut 7 tuntutan resmi yang diusung, justru menggotong pataka-pataka yang sama sekali tidak berhubungan dengan tuntutan yang ada yang menyuarakan kegelisahan pribadinya. Spanduk-spanduk bertuliskan “IPK saya abaikan demi melindungi kemaluan pacarku”, “Negara Kolonial Republik Investor (NKRI)”, “Adakah AWM bosku?? #JanganPakaiPeluruAsliPak”, “Sange dikit kena pasal” dan lain sebagainya mewarnai iring-iringan pawai mahasiswa dan aksi saling lempar pelajar dan masyarakat melawan aparatur represif negara.
Gelombang aksi yang mengusung tagar #ReformasiDikorupsi ini memang mengajukan 7 tuntutan resmi terkait dengan kondisi sosial politik, yang sejauh ini menjadi bahan perdebatan antara pihak pro pemerintah dan masyarakat sipil. Namun apa yang tidak dilihat oleh para orang tua yang terlibat dalam perdebatan ini adalah sebuah perlawanan lain yang eksis dalam gelombang tersebut: perlawanan pemuda terhadap budaya lama yang konservatis.
Tidak seperti yang disangka para Marxis determinis, perubahan system ekonomi tidak serta merta membawa perubahan di bidang kebudayaan. Dalam berbagai kasus, selalu terdapat budaya lama yang masih bertahan. Sebab itu, kontradiksi segera mengemuka ketika lahir generasi baru yang menuntut kebudayaan yang baru pula, menggantikan budaya lama yang sudah seharusnya runtuh bersama dengan system ekonomi yang menopangnya. Tuntutan semacam ini dapat kita temukan dalam berbagai kasus perlawanan mahasiswa di berbagai belahan dunia.
Dalam sejarahnya, perlawanan pemuda terhadap budaya tua telah terbukti benar-benar memiliki kekuatan untuk meruntuhkan budaya lama. Salah satu contoh terbaiknya dapat kita saksikan pada momen-momen pemberontakan di Paris tahun 1968, sebuah pertarungan jalanan antara polisi yang berseragam rapi dan kuno melawan para mahasiswa yang mengenakan jaket, dasi jumper yang rapi, rambut pendek dan celana ketat.
Rangkaian momen mengejutkan tersebut merupakan dampak langsung dari kebosanan pemuda yang ada di Perancis pada masa itu. Di akhir masa PD II, terdapat ledakan kelahiran bayi yang nantinya melahirkan sebuah generasi yang akan mencapai masa mudanya di tahun 1960-an. Di Perancis, peningkatan ini meningkat dari 30.7% di tahun 1954 menuju 33.8% di tahun 1968. Hal ini diiringi dengan peningkatan jumlah institusi pendidikan di Perancis, di mana yang sebelumnya terdapat 60,000 mahasiswa di tahun 1961, meningkat menjadi 605,000 di tahun 1968.
Kampus-kampus di Perancis sejak awal memang tidak hanya digunakan sebagai tempat berkuliah, namun juga digunakan oleh para mahasiswa sebagai ruang yang bebas untuk mendiskusikan dan mempraktikkan ide-ide yang mereka temukan dari buku-buku yang dilahapnya. Ruang-ruang tersebut menjadi ladang persemaian bibit-bibit pemberontakan di tahun 1960-an di mana ‘tuhan intelektual’ bagi para mahasiswa pada saat itu adalah Marx, Freud dan Sartre.
Namun, terlepas dari kebebasan ‘semu’ di kampus, para pemuda pada masa itu cenderung merasa bahwa mereka diperlakukan sebagai anak kecil dan digembala seperti domba oleh para orang tua dan Negara. Kondisi demikian, mendorong sebuah perasaan umum di kalangan pemuda yang dengan tepat diungkapkan dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Pierre Viansson-Ponté di Le Monde pada 15 Maret 1968 yang mengatakan bahwa Perancis sedang menderita sebuah musibah politik yang berbahaya: kebosanan. Kontradiksi ini, kondisi pemuda yang terjebak di antara kebosanan serta kebebasan untuk memiliki jalan hidupnya sendiri, menghadapkan mereka dengan pilihan menjalani hidup berdasarkan dikte orang tua dan budaya tua yang membosankan atau menyusun ulang pandangan hidupnya sendiri, yang mana merupakan kebebasan yang ‘memabukkan’ untuk dijalani.
Di Paris, kebosanan ini menjadi bom waktu yang akhirnya meledak menjadi suatu pemberontakan para pelajar dan mahasiswa di tahun 1968. Kekhawatiran Viansson-Ponté benar-benar terbukti. Para pemuda telah memilih pilihan untuk meninggalkan budaya tua yang menjadi sumber kebosanan mereka. Perlawanan terhadap kebosanan ini yang dengan dipersenjatai oleh kekuatan terbesar di dalam masyarakat, yakni buruh sebagai penyuplai tenaga kerja bagi perusahan-perusahan, berhasil meningkat menjadi sebuah gangguan hebat bagi system politik yang sedang berkuasa.
Diiringi dengan tuntutan para pekerja terkait beberapa kebijakan yang jelas seperti kondisi kerja yang sehat, peningkatan upah dsb, mahasiswa dengan tuntutan yang sangat buram, yang lebih bersifat filosofis ketimbang politis, tuntutan yang kadang dibalut dengan sentimen seksual dan rasa frustasi atas kehidupannya, justru bertransformasi menjadi tuntutan yang realistis untuk diwujudkan pada masa itu. “Realistislah, tuntut yang tidak mungkin!”, “Realisasikan hasratmu!”, “Lepaskan kancing otakmu seperti kau lepaskan kancing celanamu”. “Ekonomi sedang sekarat. Biarkan ia mati”, “larilah kawan, dunia lama ada dibelakangmu!”, “kami tidak menginginkan apa-apa dari dunia yang menjanjikan kepastian untuk tidak mati kelaparan namun dipertukarkan dengan resiko mati karena bosan.” Menjadi tuntutan-tuntutan yang coba direalisasikan dalam pemberontakan tersebut.
Pemberontakan yang terbesar sejak masa revolusi Perancis ini pada awalnya hanyalah merupakan tuntutan para muda-mudi agar dapat bebas untuk tidur satu ranjang dengan lawan jenisnya. Seiring waktu, tuntutan tersebut beranjak menjadi momen di mana ribuan pekerja penduduki pabrik-pabrik tempatnya bekerja, mahasiswa dan pelajar mengambil alih control atas kampus dan sekolahnya, dan seluruh masyarakat terlibat dalam perang jalanan melawan polisi selama sebulan penuh. Para politisi yang sedang menjabat di masa itu benar-benar tidak paham apa sebenarnya yang sedang terjadi. Betapa tidak, pertumbuhan ekonomi di masa itu sangat kuat, Negara dalam keadaan stabil dan tenang, baik secara politik maupun sosial, tingkat inflasi rendah, standar hidup meningkat dan hanya terdapat sedikit pengangguran.
Pemberontakan ini dimulai pada tahun 1966 di Universitas Strasbourg, ketika panflet yang berisi kritik terhadap mahasiswa dan universitas serta analisis terhadap masyarakat modern berjudul “Tentang Kemiskinan Hidup Mahasiswa: Dipertimbangkan dari aspek ekonomi, politik, psikologi, seksual, dan khususnya aspek intelektualnya, beserta sebuah tawaran mengobatinya” disebarkan oleh beberapa mahasiswa pro-situ[1] di hari pertama masuk kuliah. Konsekuensinya, para mahasiswa yang diduga bertanggungjawab atas penyebaran panflet tersebut harus menjalani sidang di pengadilan atas tuduhan subversive. Skandal ini segera memancing keributan di seluruh Kota Paris, dan membangkitkan sebuah kesadaran baru di kalangan para pemuda di berbagai universitas.
Konsekuensi langsung dari skandal Strasbourg tersebut pertama kali terlihat di asrama-asrama universitas di Jussieu, sekitar daerah Lyon, pada musim panas tahun 1967 dimana selama beberapa minggu para penghuninya yang merupakan mahasiswa melakukan pembangkangan terhadap aturan asrama. Kejadian ini menjadi bentuk perlawanan pertama setelah sebelumnya isu reformasi aturan anti seksual di kampus ramai diperbincangkan. Menyusul kejadian tersebut, di awal Desember 1967, mahasiswa Nantes beranjak lebih jauh dengan melakukan pertukaran tempat antara mahasiswa laki-laki di asrama perempuan dan sebaliknya.
Kejadian-kejadian ini kemudian menginspirasi perlawanan-perlawanan yang lebih besar di tingkat universitas, yang belakangan memperluas tuntutannya menjadi demonstrasi anti-perang Vietnam di sekitar bulan Maret 1968. Pada aksi tersebut, beberapa mahasiswa Universitas Nanterre ditangkap. Penangkapan ini disikapi oleh 150 pelajar radikal, beserta beberapa seniman dan musisi, dengan menduduki bangunan administrasi sekolah. Pada momen inilah pergerakan 22 Maret terbentuk dan melancarkan serangkaian aksinya dan menimbulkan keributan di kampus-kampus.
Sebagai dampak dari kekacauan yang terjadi antara mahasiswa dan kepolisian, yang diberitakan oleh media-media Perancis, para pekerja mengambil sikap dan membangun solidaritas dengan mahasiswa. Hal ini kemudian memicu ledakan pemogokan dan pemberontakan buruh di pabrik-pabrik di berbagai daerah di Perancis. Merespon hal tersebut, pemerintah mencoba menenangkan suasana dengan membebaskan para mahasiswa yang ditahan, yang terbukti tidak berpengaruh terhadap eskalasi gerakan. Beragam pemberontakan di pabrik, universitas, sekolah, dan jalan raya terus berlanjut hingga akhir maret, ketika presiden Perancis menyerukan penyelenggaraan pemilu dan mengembalikan situasi ke keadaan semula.
Gelombang pemberontakan tahun 1968 memang tidak berhasil melakukan revolusi politik. Presiden de Gaulle nyatanya dapat kembali memantapkan posisi kekuasaannya di seantero Perancis. Namun keberhasilan utama dari gerakan ini adalah kemenangannya atas pembangunan budaya baru yang meruntuhkan pilar-pilar utama yang menopang budaya lama.

Kondisi demikian, disadari atau tidak, juga mulai terasa di Indonesia belakangan ini. Per tahun 2019, para pemuda telah merasakan kondisi kebosanan yang akut. Tidak lagi dapat terhibur oleh mall, café-café, game online, bahkan mendaki gunung dan berbagai kegiatan repetitive lainnya, pemuda kini mulai gelisah terhadap budaya tua yang masih berkuasa atasnya. Mendapati dirinya terkekang oleh para orang tua dan negara yang memaksakan etika dan budaya kolotnya, diperparah dengan absennya wadah gerakan, baik yang kiri maupun yang kanan, yang dapat mengatasi rasa frustasi dan kebosanan mereka, pemuda mulai merasakan bahwa terdapat sesuatu yang lebih dalam yang mendasari kebosanan mereka: Gap antara budaya dan norma-norma para orang tua yang monoton dan repetitive dan gaya hidup generasi milenial yang penuh kreativitas, penuh pemaknaan dan cepat bosan. Jurang yang lebar ini menemukan titik klimaksnya yang terealisasi melalui pataka-pataka pada gelombang aksi skala nasional pada September lalu, yang terus berlanjut sampai hari ini.
Dengan isu pengesahan RKUHP yang menjadi katalis bagi kemarahan para pemuda, generasi yang sering dicap para orang tua sebagai generasi ‘milenial’ ini akhirnya memutuskan untuk membanjiri jalanan di hampir seluruh daerah di Indonesia, sebuah momentum yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak reformasi 1998. Tidak lagi percaya kepada para orang tua yang selalu saja berusaha ‘mewakili’ suara mereka, para pemuda mengarahkan kemarahannya kepada DPR sebagai representasi orang tua yang sok tahu tentang segala urusan mereka.
Pada momentum tersebut, tuntutan-tuntutan yang tampak tidak heroic dan cenderung ‘tidak beradab’ menggantikan tuntutan-tuntutan yang heroic dan penuh keberadaban ala mahasiswa pada umumnya. Layaknya semangat para pelajar Paris di tahun 1968, “kami bukan pelayan masyarakat. Biarkan masyarakat melayani dirinya sendiri”. Ketimbang memperjuangkan sesuatu yang terlalu besar, para pemuda turun ke jalan untuk menyuarakan permasalahan generasinya. Tuntutan yang menurut generasi tua merupakan sesuatu yang tidak beradab ini, semakin dikonfirmasi oleh para pemuda dengan hunjaman batu ke pihak kepolisian, menandai kelahiran sebuah generasi baru yang menuntut datangnya sebuah budaya yang baru pula yang dapat memebaskan mereka dari kebosanan akut yang membelenggunya..
Dengan demikian, apakah gelombang ini hanyalah sebuah awal dari perlawanan yang lebih besar? Akankah ia bertransformasi menjadi sebuah perlawanan kultural yang dapat meruntuhkan budaya lama? Entahlah. Namun mengingat bahwa perlawanan tersebut masih berlangsung sampai hari ini, hanya hunjaman batu dan Molotov, beserta luapan cinta dan ke-‘sange’-an para pemuda, yang akan menjawabnya. Sebab, ketika seseorang telah sadar bahwa ia sedang bosan, maka sudah seharusnya mereka menghentikan kebosanannya. Cheers!
[1] Pro-situ: orang-orang yang bersepakat dengan ide-ide Situasionis. Situasionis Internasional merupakan organisasi revolusioner skala internasional berisi seniman avant-garde, intelektual, dan teoritisi politik, yang melandaskan dirinya pada Marxisme anti-otoritarian dan pergerakan avant-garde abad 20, khususnya Dada dan Surealisme. Teori-teori yang diciptakannya merupakan usaha untuk mensintesiskan beragam disiplin teoritis untuk dijadikan kritik terhadap kapitalisme pertengahan abad 20.
Penulis adalah pegiat beragam kegiatan yang dianggapnya menyenangkan di Lingkar Tidak Makan Komisariat UNHAS.












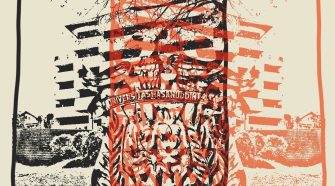
No Comment